Menyusuri Jejak Langkah Thầy

Guru Dharma Mitchell Ratner merefleksikan perjalanan ziarahnya menelusuri kehidupan dan silsilah Thích Nhất Hạnh di Vietnam, yang memberinya pemahaman mendalam tentang Thầy dan dirinya sendiri.

Pada tahun 2019, Suster Định Nghiêm bercerita kepada saya tentang sebuah ide yang terpikir di dalam hatinya. Dia merasa ada banyak biarawan dan umat awam pengikut Thầy yang tidak berasal dari Vietnam yang akan lebih memahami ajaran dan praktik jika mereka lebih mengenal sejarah Buddhis yang kaya di Vietnam serta peristiwa dan berbagai tempat yang telah menempa kehidupan Thầy. Sister Định Nghiêm dan saya kemudian memulai perencanaan awal untuk melakukan tur ziarah. Namun, karena pandemi COVID dan kesehatan Thầy yang menurun, ziarah Mengikuti Jejak Thầy yang pertama tertunda.
Setelah wafatnya Thầy pada tahun 2022 dan meredanya kekhawatiran akan COVID, Suster Định Nghiêm, bekerja sama dengan Suster Tuệ Nghiêm, merencanakan ziarah pada Januari 2023. Kelompok peziarah bertemu pada tanggal 6 Januari di rumah Hà Nội yang luas milik teman-teman Vietnam di Plum Village untuk memulai tur ziarah selama delapan belas hari; beberapa dari kami dapat berpartisipasi secara menyeluruh, dan yang lain hanya sebagian. Ada tiga puluh orang peserta – jumlah yang tepat untuk bisa nyaman berada di dalam bus wisata Vietnam. Pada pertemuan awal, ada delapan wihara di Plum Village (dari Vietnam, Perancis, Indonesia, Thailand, dan Malaysia), dua kepala biara Korea, dan sekitar dua puluh umat awam (dari Amerika Serikat, Spanyol, Perancis, Jerman, Korea, Thailand, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura). Sister Định Nghiêm dan Tuệ Nghiêm, biksuni senior dari New Hamlet di Plum Village, Prancis, menjadi tuan rumah, pemandu, sejarawan kehidupan Thầy, penerjemah, dan pembimbing kami.
Selama ziarah, kami menghabiskan malam di Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Lạt, Huế, dan Gunung Yên Tử, serta satu malam menginap di kereta malam. Sehari-hari kami sering bepergian dengan bus untuk mengunjungi tempat-tempat yang penting bagi kemajuan Thầy sebagai pribadi dan sebagai guru. Ziarah ini terkadang meliputi latihan retret dengan meditasi duduk dan berjalan; grup belajar dengan para sister pengorganisir dan pemandu lokal yang menyajikan presentasi tentang pentingnya tempat-tempat yang akan kami kunjungi; dan sebuah tempat untuk percakapan dari hati ke hati selama berhari-hari mengenai kehidupan kami dan praktik ajaran Buddha yang kami jalani. Singkatnya, sangat luar biasa!
Lima pertemuan yang sangat menyentuh hati saya dan membantu saya memahami Thầy dengan sudut pandang yang baru: Gunung Thanh Hóa dan Na, Chùa Dâu (biara Buddha pertama di Vietnam), raja-raja yang tercerahkan dari Dinasti Trần Nhân, Gunung Yên Tử, dan Kuil Từ Hiếu.
Gunung Thanh Hóa dan Gunung Na

Salah satu tujuan pertama kami adalah kota Thanh Hóa, tempat keluarga Thầy pindah saat dia berusia lima tahun. Kami tiba di pagi hari dan makan siang sederhana di sebuah restoran vegetarian kecil di bagian kuno dari kota ini, yang kebetulan memiliki sebuah kutipan dan foto Albert Einstein di sebelah meja kasir. Pada sore hari, kunjungan ke museum arkeologi membangkitkan minat saya terhadap sejarah Vietnam dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan ajaran Thầy- sebuah cara pandang terhadap dunia yang terpengaruh oleh latihan dan profesi saya sebagai antropolog sosial. Sebelum melakukan ziarah, hampir semua yang saya ketahui tentang sejarah Vietnam berada pada abad ke-20.
Fokus utama museum arkeologi di Thanh Hóa adalah budaya Dong Son, yang muncul sekitar tiga ribu tahun yang lalu di Lembah dan Delta Sungai Merah, yang secara umum sama dengan Vietnam Utara saat ini. Suku Dong Son mahir dalam bercocok tanam padi dan terampil dalam membuat peralatan perunggu. Seiring berjalannya waktu, sebuah wilayah yang luas secara geografis, hierarkis, dan memiliki struktur seperti negara muncul, dipimpin oleh para penguasa turun-temurun yang menciptakan dan memelihara sistem hidrolis untuk budidaya pertanian dan perlindungan terhadap banjir, mengelola perdagangan, dan mencegah serangan dan invasi. Antara tahun 43 dan 299 Masehi, daerah Lembah Sungai Merah yang produktif dalam pertanian merupakan bagian dari distrik administratif yang disebut Pemerintahan Jiaozhi (Quận Giao Chỉ). Meskipun penduduknya sebagian besar berbahasa Vietnam, mereka diperintah oleh dinasti-dinasti Tiongkok.

Hotel kami terletak di pusat modern Thanh Hóa setinggi sepuluh lantai dan sepi, dengan hanya sedikit tamu. Namun, kekosongan lobi sangat mendukung malam itu karena ruang makan yang terletak di sebelahnya menyediakan sinyal Wi-Fi terbaik di hotel itu. Pada pukul 21.00 waktu Vietnam, yang sama dengan pukul 09.00 di Amerika Serikat bagian Timur, saya berpartisipasi pada sebuah seremoni langsung dan online untuk mentransmisikan Latihan Lima Perhatian Penuh kepada para praktisi di wilayah Washington DC. Ketika mengakses internet di hotel dan mengingat kutipan Einstein saat makan siang, saya dikejutkan oleh betapa jauh perkembangan Thanh Hóa saat ini dibandingkan dengan kota provinsi yang Thầy kenal di tahun 1930-an.
Keesokan paginya, kami melakukan perjalanan dengan bus ke Gunung Na, salah satu dari tiga lokasi paling suci di Vietnam. Thầy mengunjungi gunung tersebut dalam sebuah perjalanan sekolah saat berusia sebelas tahun. Dia berharap dapat bertemu dengan seorang pertapa yang diceritakan oleh gurunya tinggal di gunung tersebut. Pergi sendiri, Thầy menemukan gubuk sederhana milik pertapa tersebut, tetapi tidak menemukan pertapa itu. Kemudian dia menemukan hal lain yang mengubah jalan hidupnya. Thầy menyebutnya sebagai pengalaman spiritual pertamanya. Dalam buku At Home in the World, ia menulis:
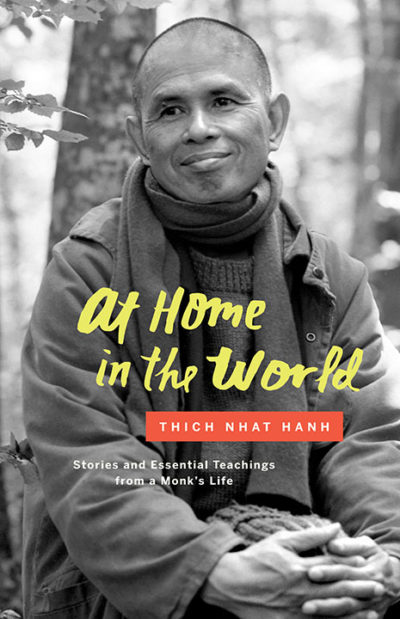
Ketika saya berjalan makin dalam ke hutan, saya mendengar suara air yang menetes. Itu adalah suara yang indah. Saya mulai mendaki ke arah suara itu, dan segera saya menemukan sebuah sumur alami, sebuah kolam kecil yang dikelilingi oleh batu-batu besar dengan berbagai warna. Airnya sangat jernih sehingga saya bisa melihat sampai ke dasar …. Airnya terasa sangat enak. Saya belum pernah merasakan sesuatu yang seenak air itu. Saya merasa sangat puas; saya tidak membutuhkan atau menginginkan apa pun – bahkan keinginan untuk bertemu dengan pertapa itu pun hilang. Saya merasa bahwa saya telah bertemu dengan pertapa itu.
Thích Nhất Hạnh, At Home in the World (Berkeley: Parallax Press, 2016), hal. 23-24.
Kelompok kami duduk bermeditasi di dekat sebuah kuil feng shui di puncak gunung. Gubuk pertapa itu sudah lama hilang. Namun, kami dapat berjalan menuruni gunung untuk berkumpul di sekitar sumur dan mencicipi airnya.
Kunjungan Thầy ke Gunung Na berkontribusi pada cita-citanya untuk menjadi seorang biksu. Ketika ia berusia enam belas tahun, ia melakukan perjalanan dengan kereta malam dari Thanh Hóa ke Huế untuk menjadi samanera di Kuil Từ Hiếu, ditemani oleh kakak laki-lakinya yang sudah menjadi biksu di sana. Kelompok ziarah kami meniru perjalanan Thầy dengan menaiki kereta malam ke Huế. Saya berbagi bilik tidur dengan para kepala biara Korea, keduanya memancarkan ketenangan yang menyenangkan yang membuat saya dan yang lainnya terkesan pada mereka. Meskipun keduanya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik, dan penerjemah wanita mereka berada di kompartemen yang berbeda, kami dapat berinteraksi dengan menyenangkan pada malam itu dan keesokan paginya dengan menggunakan isyarat dan Google Translate.

Chùa Dâu dan Guru Tăng Hội
Kemudian dalam perjalanan ziarah, kami berkendara sejauh tiga puluh mil dari Hà Nội untuk mengunjungi Chùa Dâu, Kuil Buddha pertama di Vietnam. Kuil ini dibangun antara tahun 187-226 Masehi di tempat yang saat itu bernama Luy Lâu, ibu kota Pemerintahan Jiaozhi. Karena perannya yang menonjol dalam perdagangan laut antara India dan Cina, Luy Lâu sering dikunjungi oleh para biksu dan pedagang India, dan daerah tersebut menjadi pusat regional untuk studi dan pengajaran agama Buddha Mahayana.
Bagi Thầy, Chùa Dâu sangat penting karena Guru Tăng Hội, yang meninggal pada tahun 280 Masehi, belajar dan mengajar di sana. Pada tahun 2007, setelah perjalanan pulang yang kedua kalinya setelah pengasingannya dari Vietnam, Thầy menjelaskan:
Meditasi yang saya bagikan di Barat berakar dari Vietnam pada abad ketiga. Kami memiliki seorang guru Zen yang sangat terkenal, Master Tăng Hội, yang ayahnya adalah seorang tentara dari India dan ibunya adalah seorang wanita muda Vietnam. Ketika orang tuanya meninggal dunia, Tăng Hội kecil pergi ke sebuah kuil di Vietnam utara untuk menjadi biarawan. Dia menerjemahkan komentar-komentar tentang sutra di kuil di Vietnam, kemudian pergi ke Tiongkok di mana dia menjadi guru Zen pertama yang mengajarkan meditasi di Tiongkok – tiga ratus tahun sebelum Bodhidharma. Saya menulis sebuah buku tentang Guru Zen Tăng Hội, dan saya mengatakan bahwa umat Buddha Vietnam harus mengagungkan guru Zen ini sebagai guru Zen pertama di Vietnam
Thích Nhất Hạnh, “Tiga Kekuatan Spiritual,” The Mindfulness Bell 46 (Oktober 2007)
Mengingat pentingnya Chùa Dâu bagi Thầy, kunjungan kami ke kuil tersebut berlangsung dengan cara yang mengejutkan. Kuil itu tampak jarang dikunjungi dan agak terabaikan. Meskipun terdapat patung Buddha dan Bodhisatwa, namun ada lebih banyak patung untuk memuja dewa-dewa lokal, tokoh Mandarin Tiongkok, dan roh-roh penjaga. Pemandu lokal kami dengan antusias menceritakan kisah-kisah fantastis, termasuk kisah tentang seorang wanita muda yang diubah menjadi pohon oleh seorang biksu yang tidak terhormat, kemudian berabad-abad kemudian dibebaskan oleh seorang penguasa lokal yang bijaksana yang membuat pohon yang tumbang itu dibuat menjadi patung berjubah kuning yang sekarang menjulang tinggi di atas Buddha di altar tengah. Sepanjang tur kami di kuil, para pemandu tidak pernah menyebut nama Master Tăng Hội.
Kemudian, terpisah dari para pemandu, Sister Định Nghiêm menjelaskan bahwa agama Buddha Vietnam terus hidup berdampingan dengan banyak kepercayaan dan praktik-praktik rakyat yang melibatkan dewa-dewi lokal, dewi-dewi dengan karakter ibu, dewa-dewi leluhur, dukun, dan perwujudan dari roh-roh hewan. Di beberapa kuil, seperti kuil ini, kepercayaan lain ini memiliki peran yang lebih menonjol.
Kunjungan kami ke Chùa Dâu membantu saya untuk menghargai hubungan spiritual Thầy dengan warisan Buddha Vietnam yang berusia dua ribu tahun. Karena kefasihannya berbahasa Vietnam dan Sino-Vietnam, jika ada sesuatu yang ditulis oleh seorang guru Buddhis Vietnam, ia dapat membacanya. Namun, Thầy bukan hanya seorang sejarawan dan penggemar agama Buddha Vietnam; dia juga seorang revolusioner spiritual. Sejak masa remajanya, Thầy memiliki keinginan yang dalam untuk memperbarui dan merevitalisasi agama Buddha di Vietnam. Dia ingin menjauhkan komunitas Buddhis dari takhayul dan kepercayaan rakyat yang ditentang di Chùa Dâu dan menawarkan praktik spiritual yang lebih bermanfaat, seperti yang telah disumbangkan oleh Tăng Hội kepada tradisi Buddhis.
Raja-raja yang Tercerahkan
Thầy memulai pelatihan biara di Từ Hiếu pada tahun 1942, di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Pendudukan Jepang dan penjajahan setelahnya menyebabkan banyak kesulitan bagi Từ Hiếu dan seluruh Vietnam, terutama Bencana Kelaparan Besar pada tahun 1945 ketika sekitar 600.000 hingga 2.000.000 orang Vietnam meninggal dunia. Catatan biografi Thầy:
Saat keluar dari kuil, [Thầy] melihat mayat-mayat bergelimpangan di jalanan dari mereka yang meninggal karena kelaparan dan menyaksikan truk-truk mengangkut puluhan mayat. Ketika Prancis kembali untuk merebut kembali Vietnam pada tahun 1945, kekerasan semakin meningkat. Meskipun banyak biksu muda yang tergoda oleh ajakan untuk mengangkat senjata dari pamflet-pamflet Marxis, Thầy yakin bahwa ajaran Buddha, jika diperbarui dan dikembalikan ke ajaran-ajaran dan praktik-praktik intinya, dapat benar-benar membantu meringankan penderitaan di masyarakat dan menawarkan jalan tanpa kekerasan menuju perdamaian, kemakmuran, dan kemandirian dari kekuatan penjajah, seperti yang pernah terjadi selama dinasti Lý dan Trần yang terkenal di Vietnam pada abad pertengahan
“Thich Nhat Hanh: Biografi Panjang,” Plum Village. Diakses pada 31 Agustus 2023.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kaisar-kaisar abad pertengahan yang sangat menginspirasi Thầy, kelompok ziarah kami melakukan perjalanan ke Gunung Yên Tử, tujuh puluh mil di sebelah timur Hà Nội. Tiga kaisar pertama Dinasti Trần, yang memerintah dari tahun 1226 hingga 1314, sangat mengesankan saya karena mereka adalah pemimpin militer yang efektif, penguasa yang penuh kasih, mentor yang mendukung putra-putranya, dan praktisi Buddhis yang berkomitmen penuh. Setelah kekalahan telak tentara Mongol, Trần Nhân Tông, Kaisar ketiga dari Dinasti Trần, berfokus untuk membangun kembali negaranya dan mengurangi beban orang miskin. Saat berusia tiga puluh dua tahun, dia turun tahta demi putranya. Trần Nhân Tông telah bertahun-tahun ingin mengabdikan dirinya untuk mencapai pencerahan spiritual. Setelah secara resmi menjadi “Kaisar Purnatugas”, ia meninggalkan istana untuk mempraktikkan ajaran Buddha di Gunung Yên Tử, dan ditahbiskan sebagai biksu pada tahun 1295.
Pertapaan di Antara Awan
Dalam kata pengantar untuk novel sejarahnya, Hermitage Among the Clouds, Thầy menulis tentang Trần Nhân Tông:
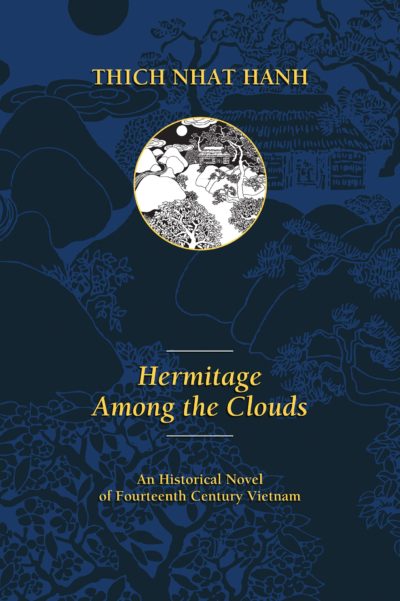
Thích Nhất Hạnh, Hermitage Among the Clouds (Berkeley: Parallax Press, 2001), hal. vii.
[Dia] melepaskan tahtanya untuk menjadi seorang biksu dan tinggal di pertapaan kecil “Awan Tidur” di Gunung Yên Tử. Dia dikenal sebagai “Guru Mulia Hutan Bambu” dan merupakan pendiri “Sekolah Meditasi Zen Hutan Bambu”.
Sebelum menjadi biksu… ia memerintah sebagai raja di tanah Viet. Dia mengusir tentara Mongol yang menyerang pada akhir abad ke-13. Sejak ditahbiskan menjadi biksu, ia menjalani kehidupan pertapa dengan mengenakan kain kasar, tidur di bawah atap dedaunan, dan pergi ke mana pun tanpa alas kaki. Bahkan sebagai seorang biarawan, ia melanjutkan pekerjaannya untuk menegakkan keadilan dan moralitas dalam kebudayaan rakyatnya. Dia melakukan perjalanan ke negeri Cham dengan harapan dapat membangun fondasi persahabatan dan perdamaian yang langgeng di antara kedua negara.
Beberapa hari sebelum kematiannya, Trần Nhân Tông menuliskan sebuah puisi di dinding kuil:
Panjangnya hidup adalah satu tarikan napas,
Thích Nhất Hạnh, Hermitage Among the Clouds (Berkeley: Parallax Press, 2001), hal. 126.
Cahaya bulan di atas ombak lautan.
Mengapa mengkhawatirkan alam Mara?
Tanah Buddha saya adalah langit musim semi.
Gunung Yên Tử
Perjalanan kelompok kami di Gunung Yên Tử dibagi menjadi dua suasana yang sangat berbeda. Kami menginap dan menyantap sebagian besar makanan di sebuah kompleks resort yang baru saja dibangun dan dibuat menyerupai biara atau kota di Vietnam pada abad ke-12. Kompleks ini terdiri dari sebuah hotel bintang lima untuk “bangsawan” serta kamar-kamar sederhana yang terdiri dari empat ranjang susun untuk “penduduk desa” (termasuk kelompok kami). Seluruh kota, dan terutama hotel bintang lima, dibuat dengan cermat dan mewah. Meskipun ada banyak pemandangan lanskap yang indah dan detail arsitektur yang indah, efek keseluruhannya bagi saya terasa tidak sesuai dengan kesederhanaan alami Gunung Yên Tử dan Sekolah Hutan Bambu yang didirikan oleh Trần Nhân Tông.
Suasana lain yang kami dapatkan adalah gunung Yên Tử: berbatu, liar, dan penuh dengan kuil-kuil Buddha dan Tao serta tempat-tempat suci. Kami mendaki Yên Tử di tengah angin yang menggigit dengan suhu sekitar sepuluh derajat Celsius. Beberapa biarawan dan umat awam mendaki selama tiga jam di tangga batu dan jalan setapak yang sangat sulit. Sisanya menerima bantuan gondola pada dua segmen. Meski begitu, perjalanan mendaki tetaplah sulit. Sepanjang perjalanan, kami melakukan sujud sembah dan meditasi berjalan di sebuah stupa dari abad ke-14 yang berisi relik-relik peninggalan Trần Nhân Tông. Pemandangan dari puncaknya adalah panorama spektakuler dari berbagai pegunungan yang tertutup awan. Kami tinggal selama satu jam, beristirahat, berbagi makanan ringan dan renungan, serta menyanyikan lagu-lagu Plum Village.


Kemudian, ketika saya berbicara dengan teman-teman tentang kaisar-kaisar Trần awal, seseorang bertanya kepada saya bagaimana ajaran dan praktik mereka dapat diterapkan pada masa kini. Pembaruan atau strategi seperti apa yang mungkin dianjurkan oleh para penguasa yang tercerahkan tersebut? Menurut saya, ini bukan tentang pembaruan atau strategi tertentu, tetapi tentang para pemimpin yang menumbuhkan dalam diri mereka dan orang lain tentang aspirasi untuk menjadi penuh kasih, welas asih, dan sadar sepenuhnya. Jika perspektif tersebut ada pada banyak orang, perubahan positif akan terjadi. Thầy mengatakan hal yang sangat mirip dalam sebuah ceramah Dharma:
Dalam ajaran Buddha, kita berbicara tentang Tiga Permata: Buddha, Dharma, Sangha. Tetapi ketika kita melihat Sangha, Permata ketiga, kita melihat bahwa Sangha mengandung dua Permata lainnya. Sangha yang baik, komunitas yang baik, terdiri dari orang-orang yang mempraktikkan perhatian penuh, konsentrasi, dan pandangan terang. …
Jadi di dalam Sangha, di dalam tubuh Sangha, karena kita memiliki Sanghakaya (tubuh Sangha) yang baik, ada banyak sel. Masing-masing dari kita adalah sebuah sel dari Sangha. Dan setiap dari kita dapat membangkitkan energi perhatian penuh, konsentrasi, dan wawasan. Dan jika setiap dari kita berlatih dengan benar, maka energi kolektif yang dihasilkan oleh Sangha akan sangat kuat.
Saya pikir kita dapat menyelamatkan planet ini, mengurangi kekerasan, dan mengakhiri perang dengan energi semacam itu. Tidak peduli seberapa berbakatnya para pemimpin politik kita, jika mereka tidak memiliki energi seperti itu, mereka tidak dapat membantu …. Martin Luther King Jr. melihat hal itu dengan sangat baik. Ia mengabdikan diri untuk membangun Sangha. Ia berbicara tentang Sangha sebagai komunitas yang dicintai. Sayangnya ia dibunuh dan tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan Sangha. Kita harus melanjutkan pekerjaannya, karena pembangunan Sangha sangat penting. Dengan pekerjaan pembangunan Sangha kita dapat menciptakan kekuatan, jenis energi, yang membantu kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan besar yang sedang kita hadapi saat ini.
Thích Nhất Hạnh, 2011, “Komunitas Tercinta,” Thích Nhất Hạnh
Wihara Từ Hiếu
Thầy tinggal di wihara Từ Hiếu di Huế selama lima tahun sebagai calon dan samanera dan kembali ke sana selama empat tahun terakhir dalam hidupnya. Ziarah kami melakukan dua kunjungan beberapa hari ke Từ Hiếu untuk berpartisipasi dalam upacara memperingati ulang tahun pertama meninggalnya Thầy dan, kemudian, untuk merayakan Tết bersama komunitas biara. Saya telah berlatih di Từ Hiếu pada tahun-tahun sebelumnya dan memiliki perasaan hangat terhadapnya karena hubungannya dengan Thầy, karena kebaikan yang saya terima dari para monastik yang berlatih di sana, dan karena sejarahnya yang menarik.

Kisah Từ Hiếu dimulai pada pertengahan abad kesembilan belas. Guru Nasional Master Thích Nhất Định adalah kepala biara yang terhormat di sebuah kuil di Huế dan juga seorang penasihat istana Dinasti Nguyễn. Ketika berusia lima puluh sembilan tahun, ia pensiun dan pindah ke sebuah gubuk jerami di hutan pinus di luar Huế. Beberapa waktu kemudian ibunya yang sudah lanjut usia, yang ia rawat di pertapaannya, jatuh sakit dan dokter menyarankan untuk makan sup ikan. Meskipun sebagai seorang biksu Buddha, beliau seorang vegetarian yang taat, Thích Nhất Định dengan patuh berjalan ke pasar setiap pagi untuk membeli ikan. Ketika orang-orang mulai menyebarkan rumor tentang pola makannya yang menyimpang, Nhất Định tidak menanggapinya.
Lama kelamaan, cerita ini sampai ke istana Kaisar Tự Đức, seorang pemimpin terpelajar dan baik hati yang merupakan pengikut kuat ajaran Konfusianisme. Dia menyelidiki dan menyadari bahwa tindakan Nhất Định didorong oleh rasa cintanya kepada ibunya. Pada tahun 1848, setahun setelah kematian Nhất Định, kaisar menghormati biksu yang setia itu dengan membangun sebuah kuil besar di lokasi gubuk jerami. Dia menamai kuil tersebut Từ Hiếu, “Kesalehan Berbakti yang Berbelas Kasih.”
Saya membayangkan biara ini sangat indah dan terawat dengan baik pada tahun-tahun awalnya, tetapi tampilan dan kondisi keuangannya mungkin jauh berkurang pada tahun 1942 ketika Thầy datang ke Từ Hiếu sebagai calon biksu. Meskipun kondisi fisiknya cukup berat, Thầy mengenang Từ Hiếu dengan penuh kasih dalam memoarnya, Jubah Guruku:
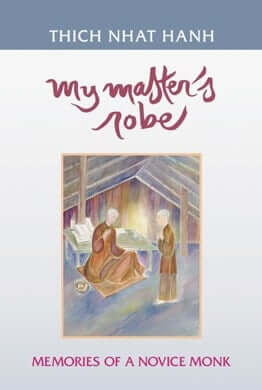
Tentu saja Anda tidak berlatih meditasi duduk sepanjang hari ketika Anda memasuki kuil. Selama berbulan-bulan dan terkadang bertahun-tahun Anda harus mengurus sapi, mengumpulkan ranting dan daun kering, membawa air, menumbuk padi, dan mengumpulkan kayu untuk api. Setiap kali ibu saya datang berkunjung dari desa kami yang jauh, ia akan menganggap hal-hal ini sebagai tantangan dari latihan tahap awal. Pada awalnya ibu saya mengkhawatirkan kesehatan saya, tetapi ketika saya semakin sehat, ia tidak lagi mengkhawatirkan saya. Bagi saya, saya tahu bahwa ini bukanlah tantangan – ini adalah latihan itu sendiri. Jika Anda memasuki kehidupan ini, Anda akan melihatnya sendiri. Jika tidak ada kegiatan mengurus sapi, tidak ada kegiatan mengumpulkan ranting dan daun, tidak ada kegiatan mengangkut air, tidak ada kegiatan menanam kentang, maka tidak akan ada sarana untuk latihan meditasi.
Thích Nhất Hạnh, My Master’s Robe (Berkeley: Parallax Press, 2005), hal. 22.

Selama perayaan Tết, kelompok kami bertemu pada suatu pagi untuk bermeditasi di “Pondok Thầy,” tempat Thầy menjalani tahun-tahun terakhirnya. Kehadiran Thầy sangat terasa. Kemudian kami pergi ke Aula Buddha untuk memberikan penghormatan kepada Buddha dan silsilah Kuil Từ Hiếu. Saya ingat berdiri, terpesona, di depan dua potret yang dibingkai bersama di ruang leluhur. Satu potret adalah guru Thầy, Kepala Biara Thích Chân Thật (1884-1968), dan di sebelah kanan adalah guru dari guru Thầy, Kepala Biara Thích Tuệ Minh (1861-1939). Potret-potret tersebut membuat saya merenungkan transmisi ajaran perhatian penuh dari generasi ke generasi, dimulai dari Buddha dan berlanjut ke Thầy dan banyak kehidupan yang telah ia sentuh dan ubah.
Potret-potret tersebut juga mengingatkan saya bahwa esensi dari sebuah latihan spiritual ditularkan melalui hubungan yang dekat dan penuh kasih. Dalam Jubah Guruku, Thầy menulis tentang menemukan gurunya terjaga hingga larut malam untuk menjahit jubah coklat. Segera Thầy menyadari bahwa gurunya sedang memperbaiki jubah tersebut sehingga dia dapat memberikannya kepada Thầy di pagi hari, ketika dia akan menerima sila samanera dan tidak akan lagi mengenakan jubah abu-abu seorang siswa baru.
Akhirnya jubah itu selesai diperbaiki. Guru saya memberi isyarat agar saya mendekat. Ia meminta saya untuk mencobanya. Jubah itu sedikit terlalu besar untuk saya, tetapi itu tidak menghalangi saya untuk merasa sangat bahagia sampai saya meneteskan air mata. Saya telah menerima jenis cinta kasih yang paling suci – cinta kasih murni yang lembut dan besar, yang memupuk dan menyirami aspirasi saya selama latihan dan praktik saya selama bertahun-tahun.
Thích Nhất Hạnh, My Master’s Robe (Berkeley: Parallax Press, 2005), hal. 97.
Terakhir kali Thầy mengunjungi gurunya di Từ Hiếu pada bulan Mei 1966, tepat sebelum Thầy melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk berbicara tentang penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh perang dan menyerukan perdamaian. Thầy menerima transmisi pelita selama kunjungan tersebut, dan menjadi salah satu dari sekian banyak pewaris Dharma dari Guru Thích Chân Thật. Dua tahun kemudian, ketika kepala biara meninggal, ia meninggalkan instruksi agar Thầy ditunjuk sebagai kepala biara Từ Hiếu. Namun, Thầy, karena kampanye perdamaiannya di Amerika Serikat, tidak diizinkan untuk kembali ke Vietnam dan tidak dapat mengunjungi Từ Hiếu lagi sampai tahun 2005.
Penyembuhan dan Transformasi
Saya mengikuti ziarah ini dengan harapan dapat memperdalam pemahaman saya tentang Thầy dan ajarannya, dan ternyata benar. Saya tidak menyangka betapa banyak hal yang bisa saya pelajari tentang diri saya sendiri.
Seperti yang telah saya sebutkan, ziarah ini membuat saya lebih sadar akan betapa dalamnya pengalaman Thầy dan diperkaya oleh hubungannya dengan para leluhurnya. Begitu saya melihat hal itu, saya mulai memperhatikannya di sekeliling saya di Vietnam: dalam lingkup ruangan dan perawatan yang dicurahkan untuk altar keluarga dan cara berkunjung ke keluarga dan kuil-kuil yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Tahun Baru Vietnam.
Semakin saya melihat dengan jelas hubungan-hubungan dengan masyarakat Vietnam ini, semakin saya sadar akan kurangnya hubungan saya dengan darah, tanah, dan leluhur spiritual saya. Kakek dan nenek saya adalah orang Yahudi Eropa Timur, pemilik toko dan penjahit, yang datang ke Amerika Serikat saat masih remaja sekitar tahun 1900. Mereka meninggalkan komunitas tempat mereka dibesarkan, bahasa yang biasa mereka gunakan, orang tua dan keluarga besar, serta tradisi spiritual yang telah memelihara generasi sebelumnya. Tak lama setelah saya lahir, orang tua saya pindah dari Midwest ke California, memisahkan diri dari keluarga besar mereka. Saya tumbuh tanpa akar, tidak bahagia, dan tanpa rasa kepemilikan di lingkungan mana pun. Mencari sesuatu yang lebih baik, dan ingin menjauhkan diri dari tekanan keluarga, saya pindah dari California ke daerah Washington DC pada usia dua puluhan.
Saya bergumul dengan ketidakberdayaan saya selama dua dekade, dan kemudian saya bertemu dengan Thầy pada tahun 1990. Saya menyadari bahwa saya memiliki penyakit spiritual yang bahkan saya tidak tahu cara menceritakannya. Tetapi Thầy memahaminya, dan dia (dan Buddha) memiliki obatnya. Thầy menawarkan kepada saya sebuah visi tentang kehidupan yang seutuhnya dan otentik, praktik-praktik konkret untuk mengembangkan perhatian penuh dan welas asih, serta sebuah komunitas sahabat spiritual. Dengan kata lain, Buddha, Dharma, dan Sangha.
Sering kali selama ziarah, saya berpikir mengenai hampir empat puluh tahun di mana Thầy tidak dapat mengunjungi Vietnam. Ia sangat mencintai negara dan sejarahnya; ia sangat peduli pada banyak teman dan gurunya di Từ Hiếu di seluruh Vietnam yang telah mendukung dan menjaganya. Betapa menyakitkan baginya untuk berpisah dengan mereka. Dengan cara yang aneh, baik Thầy dan saya telah menjalani sebagian besar hidup kami di pengasingan. Pengasingannya bersifat geografis. Pengasingan saya adalah suatu bentuk keterasingan psikologis dan spiritual, suatu kemerosotan kemampuan saya untuk berhubungan baik dengan diri sendiri, orang-orang di sekitar saya, dan alam sekitar.
Untungnya, praktik-praktik yang membantu Thầy dalam pengasingannya, juga membantu saya dan jutaan orang lainnya. Dalam buku At Home in the World, Thầy menulis tentang dua tahun pertama pengasingannya:
Saya sering bermimpi berada di rumah di kuil asal saya di Vietnam bagian tengah. Saya mendaki bukit hijau yang dipenuhi pepohonan yang indah ketika, di tengah perjalanan, saya terbangun dan menyadari bahwa saya berada di pengasingan. Mimpi itu datang berulang kali kepada saya.
Thích Nhất Hạnh, At Home in the World (Berkeley: Parallax Press, 2016), hal. 13.
Seiring berjalannya waktu, ia belajar untuk menerima pengasingannya dan wawasan mendalam yang diberikan kepadanya:
Latihan saya adalah latihan perhatian penuh. Saya mencoba untuk hidup di sini dan saat ini dan menyentuh keajaiban hidup setiap hari. Berkat latihan inilah saya bisa bertahan. Pepohonan di Eropa sangat berbeda dengan pepohonan di Vietnam. Buah-buahan, bunga-bunga, orang-orang, semuanya benar-benar berbeda. Latihan ini membawa saya kembali ke rumah saya yang sebenarnya di sini dan saat ini. Akhirnya saya berhenti menderita, dan mimpi itu tidak kembali lagi. ….
Ungkapan, “Saya telah datang, saya telah pulang,” adalah perwujudan dari latihan saya. Ini adalah salah satu Segel Dharma utama Plum Village. Ungkapan ini mengekspresikan pemahaman saya tentang ajaran Buddha dan merupakan inti dari latihan saya. Sejak menemukan rumah sejati saya, saya tidak lagi menderita ….
Ketika kita sangat terhubung dengan kekinian, kita dapat menyentuh masa lalu dan masa depan; dan jika kita tahu bagaimana menghadapi kekinian dengan tepat, kita dapat menyembuhkan masa lalu. Justru karena saya tidak memiliki negara tempat asal saya, saya memiliki kesempatan untuk menemukan rumah saya yang sebenarnya.10
Thích Nhất Hạnh, At Home in the World (Berkeley: Parallax Press, 2016), hal. 13-14.
Saya sangat berterima kasih kepada Thầy yang telah menawarkan ajaran penyembuhannya kepada para praktisi Barat. Saya berterima kasih kepada Sister Định Nghiêm yang telah memvisualisasikan semua yang dapat ditunjukkan oleh ziarah Mengikuti Jejak Thầy kepada para praktisi non-Vietnam. Hal ini tentu saja menyentuh dan mentransformasi saya secara lebih mendalam dan dengan lebih banyak hal daripada yang saya perkirakan. Saya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Sister Định Nghiêm dan Tuệ Nghiêm, yang bekerja tanpa kenal lelah sebelum dan selama ziarah, dan kepada para praktisi yang luar biasa di bus ziarah yang dengan mereka saya berbagi sukacita, tantangan, dan wawasan baru.

Alih bahasa: Andi Setiawan
Sumber asli: Walking in Thầy’s Footsteps


